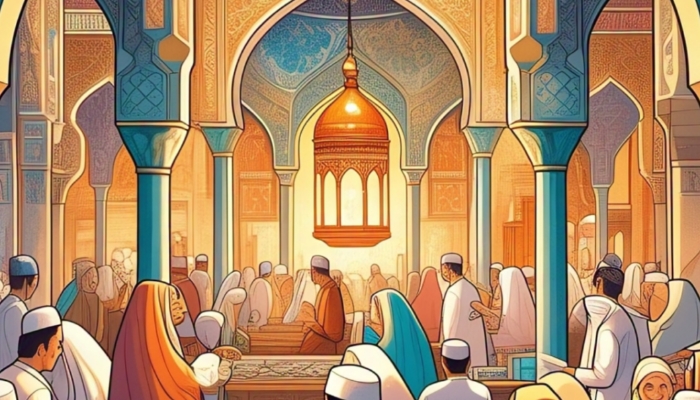Sumenep, Puisi, dan Tugu Keris: Sebuah Ironi Kekuasaan dalam Sastra

Oleh: Jufri Zaituna, penyair tinggal di Sumenep
Di antara perbatasan Sumenep-Pamekasan, tepatnya di Desa Sendang, Kecamatan Pragaan, berdiri sebuah “kuburan puisi”—bukan dalam arti harfiah, tetapi sebagai metafora atas sebuah peristiwa kebudayaan yang mengkhawatirkan.
Pada 30 Januari 2025, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, meresmikan Tugu Keris, sebuah monumen yang digadang-gadang sebagai ikon baru kota ini. Diresmikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Indonesia, tugu ini dimaksudkan untuk merepresentasikan kejayaan para leluhur, pejuang, budayawan, dan seniman Sumenep. Namun, sejak peresmiannya, polemik pun bermunculan.
Media sosial riuh dengan berbagai ulasan. TikTok, Instagram, dan media online berebut ruang untuk meliputnya, menciptakan narasi seolah-olah ini adalah pencapaian monumental bagi kebudayaan lokal. Namun, ada pertanyaan mendasar yang mengusik: apakah benar monumen ini merupakan representasi otentik dari kebudayaan Sumenep, atau sekadar instrumen pencitraan politik yang didesain untuk memanjangkan usia kekuasaan?
Puisi sebagai Ornamen Kekuasaan
Yang paling menjadi sorotan adalah puisi yang dipahat di sisi tugu, Munajat di Jantung Keris, karya Ibnu Hajar. Konon, puisi ini menafsirkan sejarah, kosmologi, dan spiritualitas Sumenep dalam lanskap metaforis yang memadukan unsur lokal dan religius. Namun, bagi banyak penyair dan kritikus sastra, puisi ini tidak lebih dari sebentuk estetika yang jinak—sebuah ekspresi yang tunduk pada hegemoni kekuasaan.
Dalam sejarah sastra Indonesia, kita mengenal penyair-penyair yang melawan hegemoni, dari Chairil Anwar yang berteriak lantang dalam Diponegoro, hingga W.S. Rendra yang menelanjangi realitas dalam Sajak Sebatang Lisong. Puisi mereka bukan sekadar rangkaian kata-kata berbunga, melainkan instrumen perlawanan.
Sebaliknya, puisi Ibnu Hajar memilih jalur yang aman. Ia tidak menantang status quo, melainkan justru memperkuatnya. Dengan diksi seperti munajat, warangka keris, dan pohon siwalan, puisi ini terjebak dalam glorifikasi tanpa daya kritis. Ia lebih merupakan upaya memperindah monumen ketimbang menggugah kesadaran kolektif.
Diksi yang Rapuh, Simbolisme yang Gagal
Dalam Munajat di Jantung Keris, terdapat baris-baris seperti:
“Dunia kita adalah gugusan luk sembilan pada kitab waktu
Di antara tajali puisi-puisi Adam yang semburat di pintu surga
Dan mari genggam warangka keris ini di halaman semesta”
Diksi seperti luk sembilan, tajali, dan warangka keris berupaya menciptakan nuansa mistis, tetapi tanpa pijakan yang jelas dalam konteks sosial-politik masyarakat Sumenep hari ini. Apakah ini sekadar permainan estetika, atau ada makna yang benar-benar ingin disampaikan?
Jika kita bandingkan dengan lirik lagu Koes Plus:
“Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.”
Lirik ini sederhana tetapi efektif. Ia menggambarkan kondisi tanah air dengan ironi yang tajam. Sebaliknya, Munajat di Jantung Keris terjebak dalam metafora yang berputar-putar, kehilangan urgensi, dan gagal membangun relasi emosional dengan pembacanya.
Sastra, Oligarki, dan Pencitraan Budaya
Fenomena seperti ini bukan hal baru dalam sejarah sastra Indonesia. Kita pernah melihat bagaimana kekuasaan menggunakan kesenian sebagai alat legitimasi. Dari masa kolonial hingga Orde Baru, sastra sering kali dijinakkan agar selaras dengan kepentingan politik.
Dalam konteks Sumenep, pemilihan puisi Ibnu Hajar untuk diabadikan di Tugu Keris mengindikasikan bahwa sastra masih ditempatkan sebagai ornamen kekuasaan. Bukan sebagai ekspresi kebebasan atau refleksi kritis, tetapi sebagai bagian dari strategi branding daerah.
Pertanyaan yang lebih besar adalah: bagaimana posisi penyair dan seniman dalam ekosistem kebudayaan ini? Apakah mereka hanya menjadi pelengkap bagi proyek-proyek monumental, atau masih ada ruang bagi mereka yang ingin menulis dengan keberanian dan ketulusan?
Sastra yang Hidup atau Sastra yang Dikanonisasi?
Jika puisi hanya menjadi bagian dari monumen, ia berisiko kehilangan daya hidupnya. Sastra yang baik tidak membutuhkan batu prasasti untuk bertahan; ia hidup dalam ingatan kolektif, dalam dialog, dalam perlawanan terhadap yang mapan.
Bagi para penyair muda Sumenep, momen ini seharusnya menjadi refleksi. Apakah mereka akan mengikuti jejak penyair-penyair yang tunduk pada proyek kebudayaan resmi, atau mereka akan menulis dengan daya kritis yang lebih tajam?
Sebab pada akhirnya, sastra yang sejati tidak akan diingat karena dipahat di batu, tetapi karena mampu mengguncang zaman.
Sumenep, 2025